MEMBACA SASTRA: MEDIUM PEMBELAJARAN MAHASISWA UNTUK MEMAHAMI TEORI SOSIAL YANG ABSTRAK
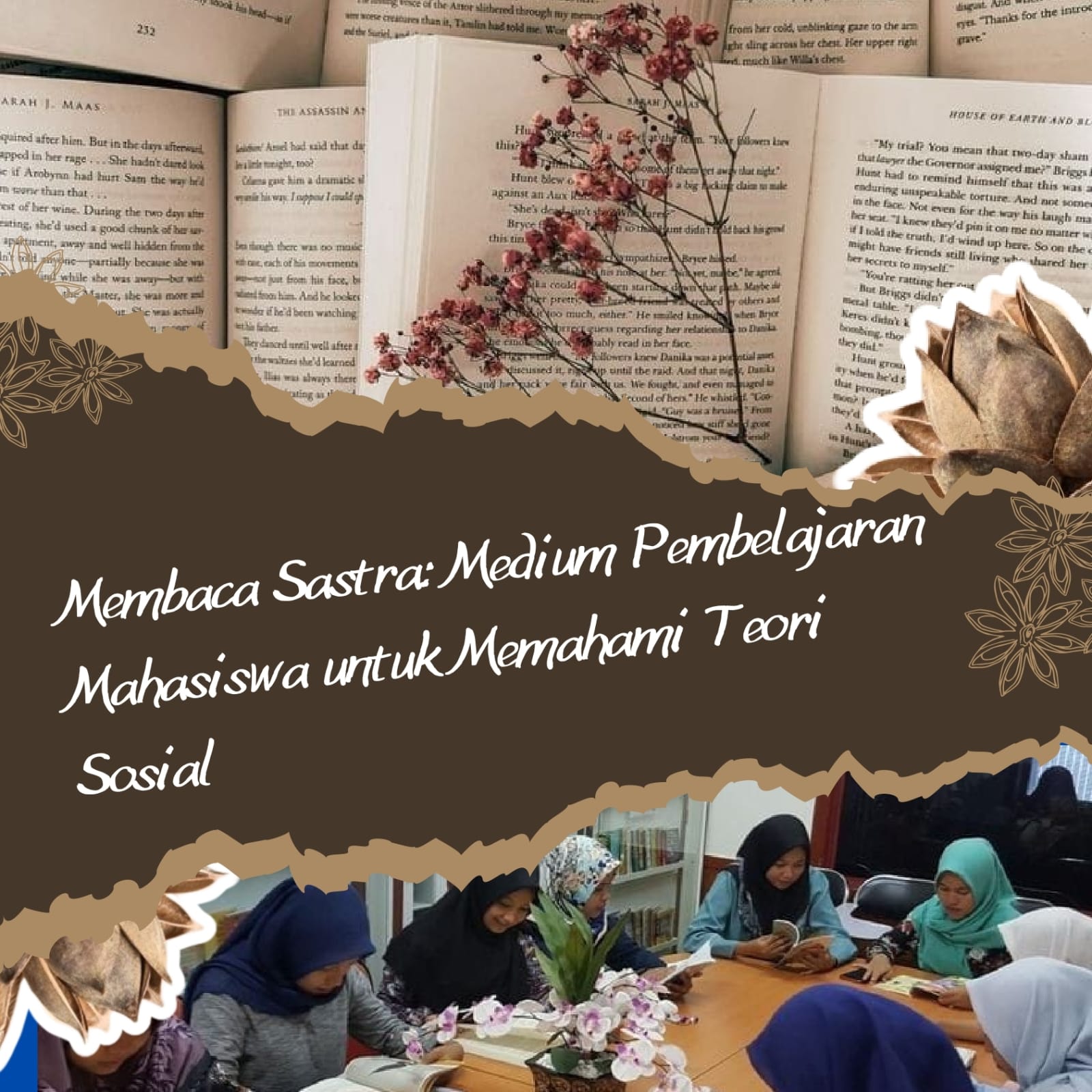
SURABAYA, sosiologi.fisipol.unesa.ac.id - Memahami teori sosial sering kali menjadi tantangan bagi mahasiswa Sosiologi. Padahal, pemahaman teori bersifat esensial dan perlu dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon sosiolog. Berdasarkan pengalaman penulis, kesulitan dalam memahami teori yang banyak dialami oleh mahasiswa semester awal, terutama mereka yang di sekolah menengah tidak pernah bersentuhan dengan pelajaran Sosiologi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, mahasiswa sering kali diarahkan untuk membaca berbagai buku teks perkuliahan. Namun, terkadang Arahan ini tidak selalu membantu. Sebab, buku-buku yang direkomendasikan cenderung akademis dengan bahasa yang kaku dan sering kali berhalaman tebal. Akibatnya, bagi pembelajar yang masih awam, buku-buku tersebut menjadi kurang menarik dan sulit dipahami. Oleh karena itu, teori-teori seperti panopticon Foucault, alienasi Marx, atau habitus Bourdieu terkadang terasa abstrak dan sulit dihubungkan dengan pengalaman.
Dalam situasi seperti ini, membaca karya sastra dapat membantu menjembatani pemahaman terhadap teori-teori sosial yang abstrak tersebut.
Imajinasi Sosiologis dan Peran Sastra
Di Indonesia, membaca karya sastra memang bisa dikatakan belum begitu membudaya. Laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2018 lalu menunjukkan pembaca sastra di Indonesia hanya sebesar 6,2 persen (Medcom.id 2018). Meskipun demikian, beberapa komunitas literasi mulai bermunculan untuk mempromosikan gerakan membaca, khususnya sastra, seperti Klub Baca Petra, Komunitas Suku Sastra, Lingkaran Sastra Kedoya, dsb.
Masyarakat umumnya menganggap kegiatan membaca sastra hanya sebagai pengungsi dari kehidupan nyata. Apalagi dalam beberapa kasus, manfaatnya disepelekan dengan manfaat membaca karya tulis lain, seperti nonfiksi maupun buku pengembangan yang lebih berorientasi praktis. Padahal, sebuah karya sastra bukan sekedar media penghiburan saja dan karya tersebut juga tidak diciptakan di ruang hampa yang terpisah dengan konteks serta situasi sosial yang melingkupinya.
Di luar ruangan perannya sebagai media hiburan, sastra memiliki fungsi sosial lainnya. Yakni, sastra memiliki hubungan representatif dengan realitas yang berkembang di masyarakat (Artika, 2022: 37-40). Ini berarti bahwa sastra merepresentasikan realitas. Apa yang tercermin dalam sastra sangat mungkin merupakan gambaran kondisi, realitas, maupun pemikiran yang ada dan berkembang di masyarakat. Hubungan inilah yang menjadi indikator utama kebenaran dalam sastra.
Jurnalis sekaligus sastrawan kawakan Indonesia, Seno Gumira Ajidarma, bahkan menyematkan dan mentransmisikan dengan lantang: ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara! Hal ini menjadi penguat adanya sastra ternyata mengandung sisi kebenaran (realitas) dari masyarakat sendiri (Ajidarma 2005).
Adapun C. Wright Mills, sosiolog Amerika, dalam karyanya The Sociological Imagination (1961) menekankan bahwa seorang sosiolog harus mampu melihat keterkaitan antara biografi individu dan realitas sosial yang lebih luas. Sastra, dengan kemampuannya menghadirkan beragam kisah dan pengalaman kehidupan dalam berbagai latar sosial historis, memberikan kesempatan bagi pembaca untuk mengalami kehidupan orang lain dan memahami kompleksitas struktur sosial yang membentuknya.
Misalnya, novel 1984 karya George Orwell, seorang sastrawan Inggris, menawarkan gambaran konkret tentang bagaimana pengawasan dan kontrol negara terhadap individu yang bekerja dalam masyarakat totaliter. Jika ditilik, apa yang dijelaskan Orwell dalam novelnya memiliki kesamaan dengan teori panopticon dari Michel Foucault. Teori tersebut pada dasarnya menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme pengawasan yang tidak selalu terlihat, tetapi tetap efektif.
Dengan membaca karya sastra seperti tahun 1984, mahasiswa dapat melihat bagaimana teori yang tampak abstrak dalam sastra akademik sebenarnya dapat ditemukan dalam representasi budaya populer. Melalui kisah yang termuat dalam karya tersebut, mahasiswa juga lebih mudah membayangkan sekaligus menghubungkan teori dengan pengalaman sehari-hari.
Dalam hal ini, peran sastra mengarah pada medium yang dapat mengasah kemampuan berimajinasi mahasiswa. Karena seperti yang dijelaskan (Mills 1961), kemampuan mengabstraksikan sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan melakukan pembayangan atau berimajinasi untuk menjelaskan fenomena. Oleh karena itu, mengapa tidak memanfaatkan sastra?
Sastra Sebagai Penunjang Pembelajaran Sosiologi
Dalam dunia akademik yang semakin spesialis dan berorientasi praktis, membaca sastra mungkin tampak seperti kegiatan yang tidak relevan bagi mahasiswa Sosiologi. Namun justru sebaliknya—sastra dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pemahaman terkait teori dan memperdalam analisis mahasiswa terhadap realitas sosial, di samping itu dapat menumbuhkan imajinasi dan kepekaan.
Dengan menggabungkan bacaan akademik dan karya sastra memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori dalam bentuk abstrak, tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut bekerja dalam kehidupan nyata. Dengan mengembangkan imajinasi sosiologis melalui sastra, mahasiswa Sosiologi dapat menjadi lebih peka terhadap dunia sekitar dan lebih siap dalam menganalisis serta merespons perubahan sosial.
REFERENSI :
Ajidarma, Seno Gumira. 2005. Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara. Edisi ke-2. Yogyakarta: Bentang Pusaka.
Artika, I. Wayan. 2022. Buku Praktis Sosiologi Sastra . Denpasar: Pustaka Larasan.
Medcom.id. 2018. “Survei: Pembaca Sastra Indonesia Hanya 6,2%.” Diakses ( https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNgJ8ZRK-survei-pembaca-sastra-indonesia-hanya-6-2 ).
Mills, C. Wright. 1961. The Sociological Imagination. New York: Grove Press Inc.
Penulis: Elrisa Diana K.
Editor: Nicodemus Daniello Nazon Sereh